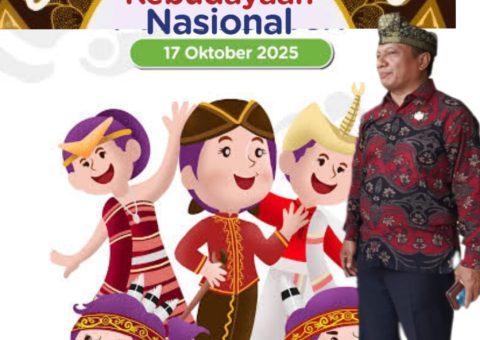Oleh : Sendy Alpagari
Dinamika Pertumbuhan dan Demografi
Pekanbaru hari ini dikenal sebagai pusat ekonomi, pemerintahan, dan budaya di Provinsi Riau. Berdasarkan data pertengahan 2024, penduduknya mencapai sekitar 1,12 juta jiwa, setara 16,37% dari total penduduk Riau yang berjumlah ± 6,86 juta jiwa. Angka ini menegaskan peran Pekanbaru sebagai magnet urbanisasi, bukan hanya bagi masyarakat Riau sendiri, tetapi juga bagi pendatang dari berbagai daerah lain di Sumatra. Kepadatan penduduk, mobilitas tinggi, dan kemajuan infrastruktur membuat Pekanbaru berdiri sejajar dengan kota besar lain di Indonesia.
Perjalanan panjang kota ini tidak lepas dari sejarah administrasi yang kompleks. Pada masa kolonial Belanda, wilayah yang sekarang menjadi Pekanbaru masih berada dalam lingkup Kabupaten Kampar. Setelah Indonesia merdeka, statusnya berubah berulang kali: dari “kota kecil” melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, kemudian menjadi Kota Praja, dan akhirnya resmi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959. Penetapan ini berlangsung setelah Pemerintah Pusat memutuskan memindahkan ibu kota provinsi dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, mengingat letaknya yang strategis di jalur transportasi darat dan sungai.
Pertumbuhan ekonomi Pekanbaru sejalan dengan lajunya jumlah penduduk. Data Pemerintah Kota tahun 2024 mencatat lebih dari 2 juta wisatawan domestik dan 31 ribu wisatawan mancanegara berkunjung dalam satu tahun. Sektor jasa, perdagangan, dan industri kreatif berkembang pesat, menjadikan Pekanbaru sebagai pusat pertemuan bisnis dan kebudayaan di bagian tengah Sumatra. Program pelestarian 30 cagar budaya dan event seni seperti “Pekan Budaya Kreatif” menunjukkan keseriusan pemerintah kota mengangkat identitas historis sebagai daya tarik wisata dan ekonomi.
Identitas Budaya yang Majemuk
Meski demikian, identitas budaya Pekanbaru tidak bisa dipandang tunggal. Sejarah kota ini dibentuk oleh berbagai komunitas yang datang dan berinteraksi: masyarakat Kampar sebagai penduduk awal, migran dari pesisir timur Sumatra, hingga kelompok urban dari berbagai provinsi lain. Narasi yang menyebut Pekanbaru semata-mata “kota Melayu” terlalu menyederhanakan kenyataan. Bahasa yang digunakan warga sehari-hari lebih cair: dominan bahasa Indonesia dengan berbagai logat, sementara pemakaian bahasa Melayu lokal cenderung terbatas pada acara resmi atau seremonial.
Kenyataan sejarah juga menunjukkan bahwa Pekanbaru berdiri di atas lahan yang dulu dikelola oleh para pemimpin adat yang disebut batin. Di kawasan Senapelan, misalnya, kepemimpinan batin bersifat matrilineal—garis keturunan dari pihak ibu—yang berbeda dari stereotip budaya Melayu yang umumnya patrilineal. Struktur adat ini menandakan adanya sistem sosial yang khas sebelum kebijakan negara modern diberlakukan. Sayangnya, dokumentasi akademik mengenai komunitas batin masih sedikit, membuat generasi muda rentan menerima klaim sepihak yang tidak selalu sesuai dengan fakta sejarah.
Dalam beberapa dekade terakhir, kebijakan pelestarian budaya kadang terjebak dalam politik identitas. Misalnya, sebagian pihak mendorong penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama di ruang publik, termasuk di Bandara Sultan Syarif Kasim II, dengan alasan historis. Namun, data demografis memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat kota lebih fasih berbahasa Indonesia atau dialek lain. Klaim tunggal semacam ini menunjukkan perlunya dialog yang lebih jujur tentang identitas kota yang majemuk.
Kota Urban yang Terus Berkembang
Pekanbaru yang kita lihat sekarang merupakan kota urban yang terus bertumbuh. Arsitektur modern berdampingan dengan situs bersejarah seperti Masjid Raya An-Nur dan Rumah Tuan Kadi. Jalan-jalan protokol menampilkan wajah kota metropolitan, sementara gang-gang lama menyimpan memori perdagangan sungai yang dahulu menjadi nadi perekonomian. Perpaduan lama dan baru inilah yang menjadi kekuatan Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan dan bisnis.
Ke depan, tantangan utama Pekanbaru bukan hanya mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merumuskan kebijakan budaya yang inklusif. Pemerintah daerah bersama komunitas akademik, seniman, dan tokoh adat perlu menelusuri kembali arsip dan cerita lisan untuk memperkaya pemahaman sejarah. Dengan demikian, identitas Pekanbaru dapat dipresentasikan secara jujur: sebagai kota yang lahir dari interaksi berbagai etnis dan tradisi, bukan hasil klaim tunggal.
Jika upaya ini dijalankan, Pekanbaru berpeluang menjadi contoh kota yang memadukan kemajuan urban dengan kejujuran sejarah. Pembangunan fisik dapat berjalan seiring pelestarian nilai-nilai lokal yang majemuk, memberi inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia yang juga berhadapan dengan kompleksitas identitas.